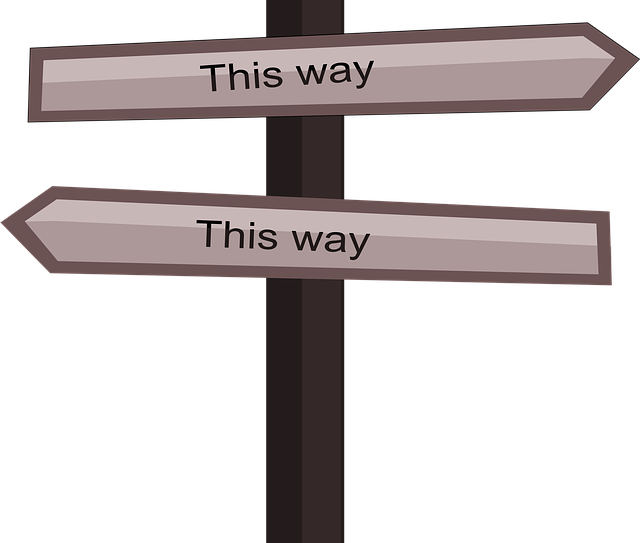Oleh Pamungkas Ayudaning Dewanto*
Dengan perasaan penuh ketidakpastian, Katri memberanikan diri untuk berangkat ke Malaysia. Sebelumnya ia tak memiliki pengalaman bepergian jauh. Jangankan ke luar negeri, ke seberang pulau pun ia tak pernah. Keberangkatan Katri tidak serta-merta wujud kemauan individu, apalagi umurnya masih 16 tahun. Selain tidak mengantongi ijazah yang cukup untuk melamar pekerjaan formal yang ada di kampungnya, ia juga tengah menghadapi masalah keluarga yang berat. Saat itu, yang ada di kepalanya hanya “aku harus pergi dari kampung ini.” Katri melihat teman-teman dan misannya yang nampak sibuk dan berpakaian serba mewah ketika pulang dari perantauan. Ia pun tak berpikir panjang dan segera mencari Warsan, juragan tembakau yang kerap menjadi sponsor bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri. Konon berangkat secara resmi tidak memerlukan modal apapun. Sebelumnya, Katri tahu bahwa melalui Warsan, Indah yang merupakan kawan sebangkunya saat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat disulap umurnya tiga tahun lebih tua menjadi 19 tahun sehingga sukses berangkat dan kini bekerja di Malaysia.Kisah Katri merupakan salah satu keadaan yang lazim kita temui di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Katri yang kurang pengalaman dan menghadapi berbagai persoalan di rumah, memaksakan diri mengambil jalan hidup yang bahkan tidak pernah terbayang di kepalanya. Walaupun bersama-sama dengan rombongan, suasana psikologis yang ia simpan ketika berangkat adalah rasa kesendirian. Ditambah, pada saat penempatan, PMI harus beradaptasi dengan suasana kerja yang asing. Lazimnya, setelah proses adaptasi, PMI dapat menjalankan hidupnya dengan tenang. Namun hal ini tidak serta merta terjadi. Pada beberapa kasus, seperti yang dialami oleh Tyas dan kawan-kawannya yang bekerja di pabrik pengolahan sarang burung wallet di Klang, Selangor. Mereka dijebloskan ke penjara lantaran dituduh masuk melalui jalur trafficking. Dalam situasi semacam ini, psikologis PMI sangatlah rawan dan labil.Pelarian dan Pengaruh Komunitas
Adaptasi tentu bukan soal mudah, sekalipun bagi mereka yang tidak memiliki beban kehidupan. Dalam menjalani adaptasi, umumnya PMI membutuhkan “pelarian” atau tempat untuk merasakan kembali kampungnya di perantauan. Mereka cenderung menciptakan kembali ruang-ruang nostalgia berada di kampungnya. Pertemuan peran PMI sebagai individu yang bekerja di negara perantauan serta fakta bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dari desa atau daerah yang sama, membentuk berbagai komunitas atau organisasi yang berlandaskan nilai-nilai kedaerahan, atau bahkan keagamaan. Dalam istilah akademik, Peggy Levitt dan Nina Glick-schiller menyebutnya dengan persilangan antara ‘peran sosial’ (ways of being) dan ‘peran simbolik’ (ways of belonging) yang dimiliki oleh setiap perantau. Akibat dari kuatnya ikatan solidaritas berdasarkan tempat asal di luar negeri inilah yang, dalam istilah Smith & Guarnizo (1998), memperkuat gerakan ‘transnasionalisme dari bawah’ (transnationalism from below). Yang menarik, hingga dua dekade lalu, transnasionalisme dari bawah masih dianggap sebagai “unsur pelengkap bagi ruang internasional yang selama ini diisi oleh interaksi antar negara-negara berdaulat.” Kini, dengan penguatan teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, serta keroposnya batas-batas negara, jejaring komunitas bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi juga arus utama dalam ruang-ruang internasional. Jejaring PMI bersifat lintas batas. Bukan hanya soal pengiriman uang ke kampung, namun juga nilai dan idealisme yang bergerak dari satu wilayah penempatan ke kampung halaman, atau juga sebaliknya (social remittance). Temuan Rachel Silvey (2004), misalnya, menunjukkan bahwa banyak di antara rumah-rumah PMI di Timur Tengah asal Rancaekek, Bandung, menyerupai kemegahan arsitektur a la jazirah. Masuknya arsitektur semacam ini menjadi indikasi kuat bahwa pekerja menjadi agen pembawa nilai dari perantauan. Jejaring yang dibangun oleh PMI ini memiliki struktur modalitas yang mengakar pada masyarakat. Oleh karenanya, komunitas PMI merupakan insfrastruktur jaringan yang sangat memadahi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Inilah yang mengakibatkan jejaring PMI kerap ditunggangi oleh kepentingan ideologis lain, termasuk oleh kepentingan kelompok tertentu yang ingin para pekerja migran menjadi individu yang radikal dan seolah berlandaskan agama. Sebagai contoh, banyak di antara komunitas-komunitas PMI ini yang kemudian aktif mengadakan berbagai kegiatan pengajian rutin demi membebaskan rasa rindunya terhadap kampung halaman. Sayangnya, penelitian yang dilakukan oleh Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC) di Hong Kong, menunjukkan telah banyak forum pengajian yang lebih dari sekedar membahas ilmu agama dan memperbaiki akhlak. Forum-forum tersebut yang mengajarkan dan bahkan memaksakan pemikiran eksklusif, chauvinistik, dan jika perlu, membenarkan kekerasan yang berbasiskan agama. Yang sangat miris, gerakan dakwah semacam ini telah bergeser dari ruang-ruang ibadah menuju pusat berkumpulnya PMI, seperti di Victoria Park, Hong Kong. Dalam situasi seperti itu, aspirasi PMI untuk mengenang kembali suasana di kampung halaman melalui komunitas justru dibajak oleh pihak tertentu untuk mewujudkan cita-cita, misalnya, ke-khalifah-an. Ditambah lagi, keterbatasan pengetahuan PMI karena kurangnya pengalaman organisasi menjadikan mereka sasaran empuk propaganda nilai-nilai radikalisme. Di sinilah terdapat kegundahan yang mendalam bagi PMI dalam menegosiasikan aspirasi yang tak simetris, antara keinginan mereka yang sesungguhnya dengan tujuan komunitas yang ada. Anggani, misalnya, eks-PMI yang telah menetap di Desa Kepanjen di Banjarnegara Jawa Tengah bahkan mengaku diintimidasi saat hendak berhenti dari aktivitas pengajian yang pernah ia ikuti di Malaysia. Sebelumnya ia sempat ditawari pekerjaan dengan upah yang cukup menjanjikan di kampung halaman, yaitu dengan berdakwah menyebarkan paham tertentu. Seiring dengan menguatnya mobilitas ide dan fisik dari satu tempat ke tempat lain akibat kemajuan teknologi, semakin menguat pula sumber daya yang bisa dikerahkan, tidak terkecuali bagi dan oleh kelompok radikal. Penyebaran dan proses indoktrinasi dilakukan, salah satunya, melalui konten-konten Youtube ataupun video yang diunggah ke dalam laman tertutup di media sosial. Sebuah film dokumenter karya Noor Huda Ismail (2016) bertajuk “Jihad Selfie”, menunjukkan para simpatisan bertransformasi menjadi relawan hanya karena ketakjubannya oleh bahasa-bahasa provokatif-dogmatis dan kebanggaan memegang senjata. Namun demikian, radikalis memang mengincar mereka yang tengah mengalami pergolakan psikologis dan yang tidak mapan secara ekonomi. Dua tipologi tersebut, sayangnya banyak ditemui di kalangan PMI. Jika kampanye dan indoktrinasi melalui ruang-ruang privat media sosial membuat pemikiran para penggunanya berubah, sosialisasi dan edukasi langsung seperti melalui pertemuan komunitas membuat keduanya lebih efektif paripurna. Di sinilah pentingnya kewaspadaan di kalangan PMI.Pencegahan
Sebetulnya, di negara tujuan seperti Malaysia telah ada pelarangan atas paham-paham radikal. Tidak jarang kita temui daftar organisasi yang dilarang oleh Kerajaan Malaysia ditempel pada papan pengumuman di masjid-masjid atau surau-surau. Kerap kali, justru organisasi yang berlenggang bebas di Indonesia masuk dalam daftar ini. Meski demikian, di manapun itu, pemantauan atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bukanlah perkara mudah. Pergerakan ‘dari bawah’ sebagai karakter utama jejaring radikalisme ini membuat mereka sulit untuk dideteksi atau dicegah. Di sisi lain, cara-cara tradisional justru berfungsi sebagai penyaring dan pengawas beredarnya paham radikal. Sebagai misal, kekentalan ajaran thariqah naqsabandiyah, tahlil dan peringatan maulid nabi di kalangan PMI asal Madura menjadi alat kontrol ideologis guna mencegah pergeseran ideologi menjadi puritan. Hubungan yang erat antara ‘santri dan kyai’ mencipta loyalitas di kalangan PMI asal Madura untuk tidak takluk pada ajaran-ajaran baru yang disebarkan oleh ulama-ulama yang tidak mereka kenal. Dalam suasana psikologis yang labil dan proses adaptasi yang ekstrem, PMI sangat rawan terjerembab ke dalam komunitas yang membawa nilai-nilai radikalisme. Kunci utama dalam mengatasi ini adalah dengan peran serta individu PMI dalam komunitas-komunitas yang memiliki berbagai kegiatan positif, menjunjung tinggi multikulturalisme dan semaksimal mungkin peduli terhadap nasib PMI yang bekerja di sekeliling kita. PMI, khususnya yang memegang dokumen resmi, mesti sadar bahwa mereka memiliki kemewahan lebih dibandingkan lainnya: mobilitas. Oleh karenanya tanggung jawab moral mereka terhadap PMI lain yang tidak berdokumen dan membutuhkan bantuan menjadi lebih besar. Dengan kewaspadaan dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan positif, ruang gerak penyebaran ajaran radikalisme akan semakin sempit.Keterangan Penulis: Dewanto Ayudhaning Pamungkas adalah Anggota Serantau Malaysia, Mahasiswa Doktoral Program Antropologi. Artikel ini telah diangkat di Warta Buruh Migran, Edisi September 2018.
Referensi
Faist T. (2000) Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture. Ethnic and racial studies 23: 189-222. IPAC. (2017) The Radicalisation of Indonesian Women Workers in Hong Kong. Jakarta: Institute for Policy Analysis and Conflict. Levitt P and Schiller NG. (2004) Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society. International Migration Review 38: 1002-1039. Malaysiakini & Tempo. (2017, Maret, 23) ‘Modern-day slavery’ at a bird’s nest factory in Klang. Malaysia Kini Special Report ed. Kuala Lumpur: Malaysia Kini. Diakses pada Oktober 9, 2018 dari https://www.malaysiakini.com/news/376686 . Mansurnoor IA. (1990) Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura: Gadjah Mada University Press. Siddiq A. (2008) The Son of the Mosque: Religious commodification within Social Relationship between Kyai and Madurese Workers in Malaysia. Center for Religious and Cross-cultural Studies. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Smith MP and Guarnizo LE. (1998) Transnationalism from below, New Bruinswick, : Transaction Publishers. Keterangan gambar/foto : Gambar/foto hanya ilustrasi, tidak menunjukkan keadaan sesunggunya yang berhubungan dengan tema tulisan.