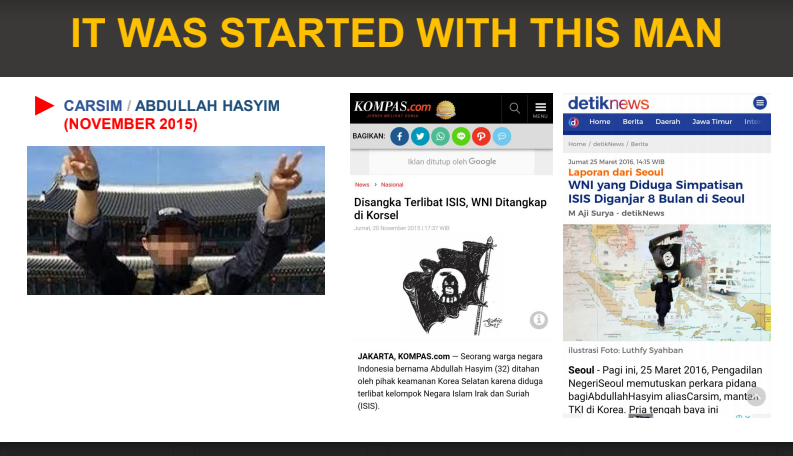Beragama yang lentur, memudahkan, dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dimana penganutnya berada, khususnya bagi pekerja migran, akan sedikit mengurangi potensi ketegangan dengan pengguna jasa.
Jika ada kelompok yang paling rentan dan bahkan memiliki kerentanan berlapis maka merekalah pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan. Kerentanan ini bersumber dari beberapa status berbeda. Pertama, status sebagai pekerja migran yang bermigrasi dari satu negara menuju negara lain yang tidak pernah dikenalnya. Kedua, status sebagai perempuan di tengah budaya patriarkhi yang memposisikan perempuan sebagai “sapu jagat” dan tulang punggung keluarga ketika ekonomi keluarga bermasalah.
Latar kekerasan berbasis gender, jeratan hutang, minimnya pelayanan dan perlindungan baik sejak berangkat dari daerah asal sampai negara tujuan menambah deret sebab kerentanan PMI. Hal tersebut ditambah dengan cara pandang masyarakat yang seringkali tidak menghargai dan merendahkan kelompok ini. Kesemua hal tersebut adalah lapisan-lapisan masalah yang membuat pekerja migran khususnya perempuan mengalami kerentanan yang berlapis. Meminjam bahasa agama, PMI perempuan berada dalam situasi “wahnan ‘ala wahnin” kelemahan diatas kelemahan baik dalam konteks sosial, ekonomi, budaya maupun perlindungan. Kerentanan ini seringkali diperparah oleh perbedaan budaya, nilai-nilai yang dianut, perbedaan agama dan keyakinan serta praktik-praktik ritual yang sangat beragam.
Berdasar temuan beberapa lembaga yang secara khusus melakukan pendampingan terhadap PMI, keragaman nilai dan perbedaan praktik keberagamaan menjadi salah satu penyebab timbulnya persoalan antara PMI dan pengguna jasa. Pekerja migran muslim yang dipaksa untuk memasak daging atau memandikan hewan yang diyakininya sebagai benda najis dan bahkan mengkonsumsi makanan yang diyakininya haram. Hal ini termasuk larangan terhadap PMI untuk melaksanakan ibadah atau mengenakan simbol-simbol tertentu ketika ibadah. Larangan pengenaan simbol-simbol agamadan larangan melakukan kewajiban-kewajiban lain yang diyakininya sebagai kewajiban agama kesemuanya berpotensi melahirkan ketegangan antara pemilik jasa dan pengguna jasa.
Memang pekerja migran sebagai manusia memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hak tersebut antara lain kebebasan beragama dan berkeyakinan yang masuk dalam wilayah eksternum sehingga tidak boleh siapa pun mengurangi apalagi menghapusnya. Dalam bahasa agama, ada kewajiban-kewajiban agama yang tidak ditawar-tawar karena ia merupakan ajaran pokok atau prinsip-prinsip dalam agama. Namun, tidak semua doktrin-doktrin yang selama ini diyakini sebagai bagian dari agama tidak bisa dikurangi atau ditawar dalam tataran pelaksanaannya. Shalat lima waktu, misalnya, bagi ummat Islam merupakan ajaran yang tidak dapat ditawar karena ia bagian dari rukun Islam (tiang peyangga Islam). Namun, bagaimana pelaksanaannya, kapan, syarat-syarat, kesunnahan-kesunnahan dan model pelaksanaannya bisa berbeda antara satu kondisi dengan kondisi lainnya, antara satu pandangan fikih (madzhab) dengan madzhab lainnya. Sebagai contoh, dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam perjalanan atau kondisi-kondisi mendesak (hajat atau dharurat) lainnya, shalat lima waktu bisa rangkap-rangkap waktunya menjadi tiga waktu saja, bahkan bisa dikurangi: yang awalnya empat rakaat bisa menjadi dua rakaat.
Rasulullah misalnya, sebagaimana disebutkan dalam hadist-hadist sahih pernah merangkap waktu shalat lima waktu menjadi tiga waktu selama 18, 19, 21 hari dalam suatu perjalanan yang beliau jalankan. Pakaian apa yang dikenakannya tidak selalu putih, kadang kuning, merah dan warna lainnya. Menarik belajar dari cerita di mana salah seorang pendiri madzhab, Asy-Syafi’i tidak membaca doa kunut ketika shalat subuh di tempat yang berdekatan dengan makam Abu hanifah, seorang pendiri madzhab Hanafiyah. Sikap Asy-Syafi’i tampak berlawanan dengan pandangan fiqihnya yang menganggap doa kunut sebagai hal yang sunnah. Namun Asy-Syafi’i melihat bahwa menghormati Abu Hanifah yang berpandangan doa kunut tidak sunnah, jauh lebih penting dari pada melakukan kesunnahan. Inilah teladan agung, bahwa dalam hal prinsip seorang perlu sikap gigih mempertahannya, akan tetapi lentur dalam cara beragama yang tidak prisip.
Beragama itu mudah, maka janganlah engkau mempersulitnya, jangan berlebihan dalam beragama karena agama pasti akan mengalahkanmu, begitulah pesan Rasulullah kepada umatnya. Doktrin agama tidaklah tunggal. Sekalipun ia berasal dari sumber yang sama, akan tetapi pemahaman dan penafsiran ulama telah memperlihatkan keragaman doktrin-doktrin agama itu. Keragaman doktrin agama karena perbedaan penafsiran ulama adalah rahmah, kasih sayang agama kepada umat manusia. Keragaman doktrin agama bukan tidak disengaja oleh Tuhan, melainkan telah direncanakan sebagai wujud kasih sayangnya untuk memberikan kemudahan dan kelenturan kepada mahluknya sesuai dengan kebutuhannya.
Pandangan tentang “apakah babi dan anjing najis?”, dimana benda yang terkena najis keduanya harus dicuci tujuh kali, salah satunya dicampur debu? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama memandang bahwa babi dan anjing tidaklah najis selama masih hidup. Sebagian ulama lain berbendapat najis, namun sama dengan najis-najis yang lain. Sebagian yang lain berpendapat keduanya adalah najis mughalladhah yang harus dibasuh tujuh kali.
Pendapat siapakah yang paling benar? Tidak ada satu pun yang bisa menjawab kecuali Tuhan sendiri, nanti di kehidupan setelah kehidupan ini. Akan mengikuti pendapat siapakah? Akankah ikut pendapat yang berat, yang paling kuat dalilnya, yang didukung mayoritas ulama atau yang paling maslahah sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Saya, lebih memilih pendapat yang terahir, yaitu bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang doktrin-doktrin keagamaan, maka ikutilah pendapat yang paling baik, paling maslahah sesuai dengan kebutuhan. Inilah praktik beragama yang pernah dicontohkan Nabi. Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda: “permudahlah jangan dipersulit, berilah kabar yang membahagiakan jangan kabar yang menyusahkan”.
Beragama yang lentur, memudahkan, dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dimana penganutnya berada, khususnya bagi pekerja migran, akan sedikit mengurangi potensi ketegangan dengan pengguna jasa. Jika misalnya pengguna jasa tidak nyaman dengan mukena warna putih, misalnya, maka kenakanlah warna mukena yang sesuai dengan budaya setempat. Jika pengguna jasa meminta bantuan untuk memasak daging, memandikan hewan yang diyakini najis, padahal ada pendapat lain yang mengatakan sebaliknya, maka mengambil pendapat yang sebaliknya jauh lebih baik dari pada bersikukuh dengan keyakinan sempitnya yang berpotensi melahirkan permusuhan. Sebab menghindarkan permusuhan adalah wajib, sementara bersikukuh pada satu pendapat adalah tidak wajib. Melakukan kewajiban lebih utama daripada melakukan seuatu yang tidak wajib.
Model keberagamaan yang ahir-ahir ini menjadi perbincangan publik karena menjadi simbol dari radikalisme beragama, adalah pengenaan cadar oleh pekerja migran muslimah. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengenaan cadar adalah bagian dari simbol keberagamaan yang dijamin dan dilindungi oleh Hak Asasi Manusia. Namun, cadar bukanlah simbol satu satunya sebagai lambang keislaman, keshalihan dan “kekaffahan” Islam seseorang. Cadar adalah wasilah atau media untuk menunjukkan kemuliaan kemanusiaan dan keshalihan seorang. Jadi yang substansi adalah martabat kemanusiaan, sementara cadar adalah medianya. Substansi tidak bisa berubah, sedangkan media bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebab itulah Imam Malik, salah satu pendiri madzhab fikih berpendapat bahwa ketika pengenaan cadar justeru melahirkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, karena telah berubah tidak lagi menjadi simbol martabat kemanusiaan, maka pengenaan cadar lebih sebagai ekstrimisme (ghuluw) dalam beragama.
Dengan demikian, diperlukan kecerdasan dan kearifan dalam beragama. Kemampuan membedakan sesuatu yang substansi dan profan turut dibutuhkan. Begitu pun, perlu upaya membedakan sesuatu yang maqhashid (red: tujuan-tujuan utama) dan mana yang wasa’il (red: media) untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuatu yang prinsipil tidak berubah, sementara bersifat turunan bisa berubah. Cara dan model beragama seperti inilah yang mampu menciptakan budaya saling menghormati di antara keragaman penganut agama. Kekakuan dalam beragama akan melahirkan klaim atas kebenaran: , menganggap dirinya paling benar dan yang lain salah dalam ruang sosial. Cara pandang terakhir inilah yang melahirkan cara ekstrimisme berpikir dan radikalisme dalam beragama. Hanya dengan sikap membuka diri dan saling menghormati yang lahir dari pemahaman agama yang luas akan tercipta toleransi beragama.[]
Sumber ilustrasi: freepik