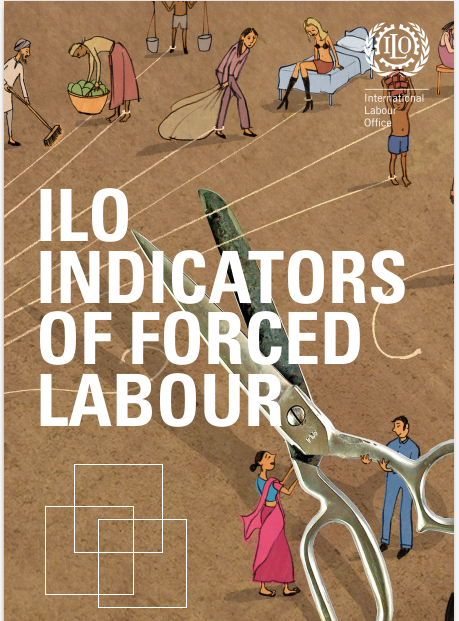Kasus Dian Yulia Novi, pelaku bom bunuh diri yang berhasil digagalkan polisi, pernah bekerja di Taiwan dan Singapura sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kasusnya menjadi pengingat bahwa radikalisme juga mengintai para PMI. Kebutuhan akan informasi keagamaan di tengah sulitnya mencari jawaban di dunia nyata, menjadi pintu masuknya kerentanan para pekerja migran.
Akhirnya, dunia maya menjadi alternatif media yang mudah diakses untuk melakukan pencarian tersebut. Ada dua alasan mengapa seseorang rentan terhadap pengaruh radikalisme. Pertama, dari sisi individu, hidup di perantauan membuat mereka jauh dari sanak keluarga serta tidak lagi bersentuhan dengan kebiasaan-kebiasan keagamaan di tanah air, menjadikan mereka gelisah dan merasa hidup ‘tidak lengkap’ lagi (McDonald, 2018). Kedua, dari segi ajaran, ada janji dan kepastian yang ditawarkan untuk menjawab kegelisahan yang sedang mereka alami.
Melalui figur karismatik, jawaban yang mudah dicerna, tawaran akan kemurnian dalam beragama, serta penebusan dosa menjadi daya tarik ajaran ini (Crenshaw, 1986). Selain itu, identitas agama yang mereka bawa dari negara asal seolah-olah dibenturkan dengan kenyataan hidup di negara perantauan. Membuat mereka merasa perlu untuk mengubah arah identitas agama (rerouting their religious identity) ke arah identitas agama yang lebih ketat dan ekstrim.
Anabel Inge (2018), seorang peneliti Salafisme di Inggris menyebut proses ini sebagai ‘reverted Muslim’ atau ‘born-again Muslim’ yaitu proses di mana seseorang menjadi Muslim yang terlahir kembali. Bahkan, mereka tidak lagi mau mengidentifikasi kehidupan mereka sebelumnya sebagai seorang Muslim dan merujuk kehidupan mereka di masa lalu sebagai zaman jahiliyah (kebodohan)(Inge 2016). Oleh karenanya, mereka yang tidak memadai secara agama, merasa hidup ‘tidak lengkap’ di perantauan, serta memiliki perasaan tidak yakin dengan arah hidup mereka adalah jenis individu yang rentan disasar oleh para perekrut aksi kekerasan mengatasnamakan agama.
Peran keluarga bagi kerentanan individu
Dalam penelitian yang saya lakukan terhadap 31 keluarga teroris di Indonesia, saya menemukan bahwa ada kontribusi keluarga terhadap rentannya individu untuk menerima sosialisasi dari luar lingkungan keluarga. Begitu juga sebaliknya, keluarga berkontribusi terhadap kokohnya identitas seseorang sehingga tidak terbawa oleh sosialisasi dari luar.
Dalam teori ‘life course’ yang dicetuskan oleh Glen H. Elder, ada tiga elemen dalam lingkungan keluarga yang menjadi faktor penting munculnya kerentanan seseorang, antara lain: struktur keluarga (family structure), hubungan keluarga (family relationship/interaction), dan sumber daya keluarga (family resource) baik sumber daya ekonomi ataupun sosial (Elder 1998). Sebagai penunjang proses sosialisasi dalam keluarga, ketiga elemen tersebut berpengaruh terhadap kemampuan individu untuk menjalankan fungsinya di masyarakat.
Sosialisasi adalah berbagai proses di mana individu diajarkan berbagai keahlian sosial, pola perilaku, serta nilai-nilai yang fungsinya dibutuhkan dalam kehidupan sosial (Maccoby 2007: 13). Dibandingkan dua elemen lain, hubungan keluarga merupakan elemen terpenting untuk menunjang suksesnya proses sosialisasi dalam keluarga.
Keluarga yang memiliki struktur tidak lengkap, masih dapat menjalankan fungsinya sebagai agen utama sosialisasi selama hubungan baik dalam keluarga masih tetap terjaga. Begitu pula dengan keluarga yang tidak berdaya secara ekonomi tetapi memiliki hubungan keluarga yang baik, juga tetap dapat melakukan sosialisasi bagi anggota keluarga. Dengan kata lain, semakin baik hubungan antar anggota keluarga, maka semakin baik pula proses sosialisasi yang terjadi (Knafo 2003; White 2000). Proses sosialisasi yang terjadi dengan baik menyebabkan seseorang menetap atau yakin dengan identitas yang mereka dapat dari sosialisasi yang terjadi dalam keluarga.
Dalam kasus terorisme, ada beberapa contoh suksesnya transmisi ideologi antara orang tua yang merupakan terdakwa teroris terhadap anak mereka yang selanjutnya mengikuti jejak mereka. Umar Jundul Haq, misalnya, merupakan anak Imam Samudra, terdakwa mati kasus bom Bali 1. Umar dikabarkan bergabung dengan Negara Islam dan meninggal di Suriah pada tahun 2015. Contoh lain adalah Hatf Saifurrasul, yang juga anak dari Saiful Anam, terdakwa kasus bom di Tentena Ambon.
Hatf terbang ke Suriah dan bergabung dengan Negara Islam di usianya yang ke 13 dan meninggal di sana. Umar dan Hatf merupakan contoh dari bagaimana ideologi diturunkan oleh orang tua sebagai sesuatu yang diyakini sebagai hal pokok dalam hidup beragama. Pola pengasuhan dan sosialisasi kedua orang tua keluarga-keluarga ini bermuara pada tujuan melakukan transmisi nilai-nilai yang disepakati bersama ke dalam bentuk aktivitas sehari-hari, seperti berinteraksi, bercerita, menonton suatu tayangan bersama dan ikut serta dalam kegiatan keagamaan orangtua. Nilai-nilai yang disosialisasikan adalah nilai loyalitas dan komitmen terhadap figur, organisasi atau ideologi tertentu.
Akan tetapi, ketika hubungan antara orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik, proses sosialisasi pun terjadi tanpa didasari tujuan untuk transmisi nilai-nilai dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini, peran keluarga ataupun orangtua sebagai agen utama sosialisasi tidak berfungsi. Indikasi disfungsi ini terjadi akibat, antara lain: permasalahan komunikasi, perceraian atau perpisahan orang tua, serta perilaku menyimpang orang tua. Akibatnya, anak tidak lagi percaya kepada orang tua dan merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Sehingga seseorang akan mengalami apa yang disebut oleh Erikson (1965) sebagai ‘role confusion’ atau kebingungan akan perannya baik di keluarga ataupun masyarakat (Erikson 1994).
Dengan tidak terjadinya proses transmisi nilai-nilai dalam keluarga, seseorang tidak memiliki loyalitas dan komitmen terhadap entitas atau ideologi tertentu yang seharusnya dikenalkan pertama kali di keluarga. Kebingungan tersebut seolah-olah menemukan solusi ketika seseorang bersentuhan dengan lingkungan di luar keluarga. Sehingga terjadilah kasus-kasus di mana pekerja migran dengan mudahnya menerima paparan dari luar tanpa melakukan crosscek terlebih dahulu.
Mengapa perlu memperkuat hubungan keluarga?
Berdasarkan penjelasan di atas, memperkuat hubungan keluarga tidak hanya berdampak pada keberhasilan orangtua dalam mentransmisi nilai-nilai yang diinginkan kepada anak, tetapi juga terhadap upaya menjauhkan anak dari dampak pengaruh luar salah satunya adalah pengaruh radikalisme. Tentu saja memperkuat hubungan keluarga bukanlah perkara instan. Dalam hal ini orang tua harus memiliki kesamaan sikap dan perilaku dalam hal menanamkan nilai-nilai. Sehingga anak tidak bingung untuk menyerap nilai mana yang harus diikuti.
Dalam beberapa program deradikalisasi yang melibatkan keluarga, kerap kali terbentur dengan berbagai permasalahan. Dalam hal ini, tidak semua jenis keluarga dapat terlibat dalam proses tersebut. Keluarga dengan kohesivitas yang baik akan lebih mudah mengajak kembali mereka yang telah terpapar. Tetapi, tidak demikian bagi keluarga dengan kohesivitas rendah. Tidak kuatnya ikatan emosional antara anggota keluarga menjadikan proses deradikalisasi menjadi perkara sulit. Oleh karenanya, memperkuat hubungan keluarga melalui perbaikan komunikasi dan ikatan emosional sejak dini diharapkan dapat mencegah para PMI dari kerentanan pengaruh radikalisme.
Keterbukaan dan saling menghargai menjadi kuncinya. Dengan demikian, ketika seseorang mengalami radikalisasi, dia akan mengalami apa yang disebut sebagai ‘cognitive dissonance’ atau ketidaknyamanan mental yang dialami seseorang yang dihadapkan pada dua atau lebih kepercayaan, ide atau nilai yang bertentangan (Festinger 1962).
Jika ajaran dalam radikalisme bertentangan dengan nilai atau ide yang selama ini didapat seseorang dari keluarga, maka sangat mungkin baginya untuk tidak terbawa arus radikalisme. Selain daripada itu, orang tua para PMI juga perlu dibekali pengetahuan mengenai bahaya radikalisme dan bagaimana mengenali tanda-tanda jika anak mereka terpengaruh radikalisme.
Sebuah studi pada anak remaja Belgia dan Belanda yang bergabung dengan Negara Islam di Suriah menemukan bahwa banyak dari orang tua para remaja ini justru malah memperlihatkan sikap tidak peduli dan menyangkal tanda-tanda radikalisasi sebenarnya telah terjadi pada anak-anak remaja mereka. Dalam hal ini, kualitas hubungan keluarga lagi-lagi menjadi penentu sikap apa yang seharusnya diambil oleh para orang tua dalam menangani permasalahan tersebut.
Keterangan Penulis:
Haula Noor adalah PhD Candidate, Department of Political and Social Change, Australian National University (ANU).
Rujukan
Crenshaw, Martha (1986), ‘The psychology of political terrorism’, Political psychology, 379-413.
Elder, Glen H (1998), ‘The life course as developmental theory’, Child development, 69 (1), 1-12.
Erikson, Erik H (1994), Identity: Youth and crisis (WW Norton & Company).
Festinger, Leon (1962), A theory of cognitive dissonance (2: Stanford university press).
Inge, Anabel (2016), The Making of a Salafi Muslim Woman: Paths to Conversion (Oxford University Press).
Knafo, Ariel (2003), ‘Contexts, relationship quality, and family value socialization: The case of parent–school ideological fit in Israel’, Personal Relationships, 10 (3), 371-88.
McDonald, Kevin (2018), Radicalization (John Wiley & Sons).
White, Fiona A (2000), ‘Relationship of family socialization processes to adolescent moral thought’, The Journal of social psychology, 140 (1), 75-91.